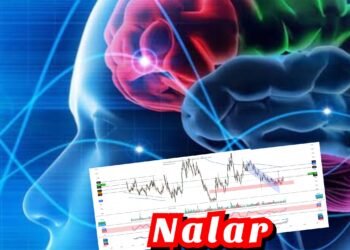Oleh: Candra Malau
“Jika untuk masuk surga saya harus membenci penganut agama lain, saya menolak menginjakkan kaki di surga.”
Demikian sederet kalimat yang dilontarkan oleh seorang pujangga India, Rabindranath Tagore. Kata-kata ini sangat menggugah hati.
Penulis sendiri tidak banyak tahu tentang dia dan berbagai karyanya. Yang penulis tahu lewat pencarian data dengan cara sederhana, ia adalah seorang penyair di India yang pernah meraih nobel dalam bidang sastra.
Terlepas dari siapa pun dia, yang pasti kalimat sarat makna yang diutarakannya sangat berkesan dan mengandung pesan moral tak ternilai, khususnya untuk bidang kemanusiaan. Sebuah cara berpikir yang bebas, tidak terjebak dalam batas doktrin tertentu, membuka diri terhadap semua golongan, dan menghargai semua perbedaan termasuk pendapat yang ada di dalamnya.
Demikianlah kira-kira secuil dari selaksa makna dalam kalimat fenomenal yang pernah terlontar dari seorang anak manusia bernama Rabindranath tersebut. Ada penolakan terhadap pengkultusan sebuah doktrin—terlebih pengkultusan dimaksud mengoyak sisi kemanusiaannya.
Sebagai manusia yang serba kekurangan, penulis mencoba untuk menuangkan pemikiran terhadap salah satu persoalan yang pernah terjadi dan (mungkin) juga belum tuntas di Indonesia, yakni persolan intoleransi. Ya, suatu persoalan yang senantiasa beririsan pada ketidaksiapan menerima perbedaan; penolakan dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
Penolakan dimaksud antara lain bisa terhadap kebudayaan, ajaran-ajaran, agama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebiasaan internal kelompok tertentu. Kondisi seperti ini beberapa kali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tentu saja, masalah yang paling akut adalah intoleransi antar-umat beragama.
Dalam perspektif penulis sendiri, intoleransi antar umat beragama ini pada dasarnya hanya dipicu oleh satu faktor, yakni tafsir yang keliru terhadap ajaran dalam agama masing-masing. Penafsiran yang keliru ini akhirnya melahirkan ego-sektoral; mengklaim diri sebagai kelompok yang paling benar.
Ajaran-ajaran dimaksud, sebagaimana lazimnya dalam setiap agama, antara lain menyangkut panutan hidup sebagai pedoman cara berperilaku, maupun cara menjalankan ritualistik-formal ibadah keagamaan.
Tujuannya tak lain adalah supaya tercipta kedamaian di tengah umat manusia dan memperoleh hidup yang kekal sesudah kematian raga—suatu narasi (umum) yang fundamen dan senantiasa dipercayai dalam agama.
Dalam tataran etimologis, secara harfiah agama memiliki arti ‘tidak kacau’. Artinya, agama itu dibuat supaya kehidupan manusia tidak kacau balau dan saling menghargai satu sama lain.
Namun ironinya, terkadang justru yang melahirkan “kekacau-balauan” itu adalah (tafsir) agama itu sendiri. Artinya, esensi dari agama itu sendiri sirna dalam kondisi ini.
Buah yang dihasilkan dari tafsir yang keliru itu secara garis besar, yaitu pemikiran bahwa ajaran yang dipahaminyalah yang tepat sebagai pedoman hidup, yang disukai oleh sang pencipta, dan jalan yang benar untuk menuju surga.
Terlebih mengenai narasi menuju surga (ya, surga saudara–saudara!). Sebuah tempat yang katanya menjadi tujuan akhir bagi orang yang percaya adanya kehidupan setelah kematian.
Namun, untuk menuju ke sana, harus ada syarat-syarat tertentu. Soal syarat inilah yang sering menjadi pemicu pergesekan antar umat beragama.
Masing-masing mengklaim bahwa untuk ke sana; harus melalui ini, tidak boleh begitu, yang boleh itu begini, tidak boleh makan itu, yang boleh itu makan ini, tidak boleh lewat situ, yang benar itu lewat sini, berkawan sama itu salah, yang benar berkawan dengan ini, surga itu di sini bukan di situ. Demikianlah kira-kira sejumlah klaimnya.
Alhasil, orang yang percaya terhadap ajaran dengan tafsir yang keliru tersebut, terjebak dalam batas-batas pengkultusan doktrin tertentu. Sehingga menganggap yang tidak sepemahaman dengan dia adalah salah. Lama-kelamaan, orang-orang seperti ini akan menganggap yang lain adalah musuh yang perlu dihabisi.
Apa yang menjadi dampak dari semua ini? Terjadi perselisihan antar umat beragama. Bukan hanya perselisihan dalam hal pendapat. Lebih dari itu, terjadi bunuh-membunuh, bakar-membakar, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
Apa yang luput dari sana? Sisi kemanusiaan kita menjadi gelap gulita. Tidak ada lagi kesadaran bahwa manusia itu adalah mahluk yang saling membutuhkan satu sama lain.
Kondisi seperti ini jelas-jelas menyimpang dari cita-cita semua agama. Tak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, pembunuhan, dan permusuhan.
Suatu waktu , penulis berdebat ringan dengan beberapa orang dari komunitas tertentu. Mereka datang dengan misi mengabarkan firman dan membuat penafsiran terhadap apa yang diutarakannya.
Dari pembicaraan salah seorang anggota komunitas tersebut, penulis menyimak bahwa dia seolah-olah mampu menafsirkan pemikiran sang pencipta. Penafsiran dimaksud adalah mengenai siapa yang masuk dan tidak masuk surga.
Dalam hal ini penulis memberi sanggahan bahwa urusan memasukkan atau tidak memasukkan orang ke surga—bagi yang memercayai hal seperti ini, adalah kuasa Ilahi. Bukan urusan manusia. Tugas manusia sebagai bagian kecil dari mahluk ciptaan-Nya adalah menjalankan perintah-Nya.
Mengasihi dan saling menghargai sesama manusia adalah hal yang paling utama dari inti ajaran setiap agama. Entah agama apa pun itu. Nilai tertinggi dari sini adalah rasa kemanusiaan.
Sebab, mengasihi ciptaan-Nya berarti kita menghargai penciptanya. Jika kita sesama manusia tidak saling menghargai, adalah sama artinya bahwa kita tidak menghargai sang pencipta.
Ada kata bijak yang berbunyi: “Kita memang tidak bersaudara dalam keagamaan, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan.” Kalimat ini dalam pandangan penulis punya kaitan dengan apa yang diuatarakan oleh Rabindranath Tagore: “Jika untuk masuk surga, saya harus membenci penganut agama lain, saya menolak menginjakkan kaki di surga.”
*Tulisan ini sebelumnya sudah pernah diterbitkan di Qureta.com.