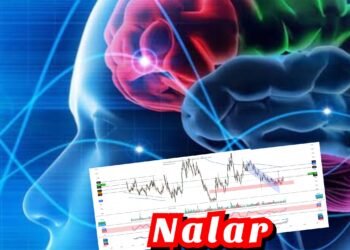Oleh :Budi P Hutasuhut*
“Hanya iblis berbentuk manusia yang mau menerima hadiah dari Nobel.”
Tahun 1952, saat panitia Hadiah Nobel memilih Bernard Shaw sebagai penerima Nobel Sastra untuk karyanya, Pygmalion, orang Irlandia ini menolaknya. Dia bukan orang kaya, hidupnya termasuk miskin. Sebagai sastrawan, dia melarat secara ekonomi. Tapi, dia punya alasan, “hanya iblis berwujud manusia yang akan menerima hadiah dari Nobel”.
Saya ingat Shaw seusai menonton “Ngeri-Ngeri Sedap” karya Bene Dion dan naskahnya pun ditulisnya. Sebuah buku tipis berjudul Kritik Film pernah ditulis Shaw, isinya tentang bagaimana sebuah karya sinematografi harus disikapi. Salah satu point penting, Shaw mengecam film-film buruk yang disiarkan kepada publik sebagai tak layak ditonton dan sineasnya seharusnya berhenti bekerja.
Saya bukan Shaw, dan buku tipis yang dihasilkannya memberi pengetahuan tentang betapa pentingnya karya seni mendapat kritik yang tajam. Sebab karya seni memiliki pengaruh luas terhadap peradaban manusia, dan kritik sebuah keniscayaan agar manusia tidak keliru hidupnya.
Sepanjang kariernya sebagai penulis (dia lebih dikenal sebagai kritikus film), Shaw nyaris mengkritik semua teks. Bahkan, kitab suci saja dia kritik sebagai teks yang paling berbahaya. Dan, sebab itu, dia tak banyak teman. Orang-orang tak menyukainya.
Bila ada pertunjukan seni dan Shaw hadir di sana, orang tidak akan melihat ke panggung, tetapi justru ke tempat Shaw duduk. Jika Shaw bertahan hingga akhir pertunjukan, itu artinya akan banyak uraian dari Shaw tentang pertunjukan iti. Namun, bila dia meninggalkan pertunjukan sebelum selesai, itu artinya sangat buruk.
Banyak seniman yang kariernya mati oleh Shaw. Dan, memang, seniman yang tak tekun dan gampang puas layak dibunuh kariernya. Apalagi seniman yang hanya mengandalkan pencitraan dan branding media sebagaimana seniman yang menjadi bagian dari industri kapitalis, yang hanya mengejar keuntungan penjualan tiket.
Di Indonesia, berlimpah seniman seperti ini. Nyaris di semua bidang seni. Mereka berkesenian untuk mengejar hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan seni itu sendiri. Tidak jarang, mereka justru menjadi agent perusak generasi bangsa, yang kehadiran karya-karyanya hanya menyebabkan rusaknya peradaban manusia.
Di dunia sinematografi, ada banyak sineas seperti itu dan sedikit yang mampu mendudukkan karya sinematografi pada posisi yang seharusnya. Film di negeri kita terlanjur dipahami sebagai medium hiburan sebelum orang betul-betul genah memahami defenisi hiburan.
Orang-orang merasa terhibur oleh mimpi-mimpi Hollywood, terhibur oleh fantasi-fantasi dan dongeng-dongeng tak rasional. Orang-orang tak tahu mendefenisikan apa yang dia tonton. Dia tak mengerti bagaimana karakter, kemampuan akting, naskah, dan unsur-unsur sinematografi lainnya. Merka tidak pernah secara tuntas memahami kenapa dalam sebuah film harus ada skenario, sutradara, kameramen, musik, ilustrasi suara, cahaya, dan lain sebagainya. Apakah semua itu berdiri sendiri, dan apakah semua itu perlu bagi sebuah film.
Ngeri-Ngeri Sedap adalah film yang tak mampu mengelaborasi tema besar yang dibayangkan Dion; “mengeksplor keresahan anak Batak terhadap orang tuanya.” Ketidakmampuan itu, pertama terlihat dari identitas Batak yang dotampilkan dalam film, yakni sebuah identitas yamg longgar lewat tokoh utama Amani Domu.
Hal yang sangat Batak pada Amani Domu cuma soal tuak dan tradisi minum tuak di lapo. Tradisi itu pun hanya selintasan dengan orang yang itu-itu saja. Seakan-akan tidak ada kekerabatan para peminum tuak, padahal kekerabatan itu sangat kental.
Sesama peminum tuak yang rutin berkumpul di lapo, punya kedekatan antara satu dengan lainnya. Mereka direkatkan oleh keakraban sebagai sesama peminum tuak yang berdiskusi perihal masalah masalah urgen dalam kehidupan. Pola komunikasi di antara mereka dibangun di atas kejujuran para pemabuk yang kehilangan sebagian kesadarannya.
Hubungan suami istri antara Amani Domu dengan Inani Domu jauh dari identitas keluarga Batak. Tidak ada orang tua Batak yang menjadikan anak-anaknya sebagai permainan, orang-orang yang harus ditipu dengan berpura-pura mau bercerai. Anak bagi keluarga Batak adalah simbol hamoraon, hagabeon, dan hasangapon. Anak itu sakral. Tidak untuk dipermainkan.
Dalam film Ngeri Ngeri Sedap, identitas keluarga pun dipermainkan. Cara anak-anak menyelesai masalah keluarga dengan menanyai ayah dan ibu secara terpisah sambil berwisata, bukan cara keluarga Batak dalam menyelesaikan masalah. Keluarga Batak punya Dalihan Na Tolu untuk menyelesaikan perkara-perkara penting dalam keluarga sapargadongan.
Ketika Inani Domu berkata kepada Amani Domu: “Bukan keluargamu yang ini yang harus kau bawa menjemput aku…”, maka ucapan itu sudah menolak nilai Dalihan Na Tolu. Pasalnya, Amani Domu membawa keluarga besarnya, Dalihan Na Tolu, untuk menjemput istrinya, Inani Domu, yang memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Jika dua pihak Dalihan Na Tolu keluarga itu sudah bertemu, tak ada alasan bagi Inani Domu untuk menolak pulang saat dijemput suaminya.
Itulah sakralnya keluarga Batak. Masyarakat Batak itu kumpulan keluarga Batak. Jika keluarga Batak seburuk keluarga Amani Domu ini, maka masyarakat Batak itu seburuk itu pula.
Penulis skenario film Ngeri Ngeri Sedap ini tak punya pengetahuan memadai tentang Batak. Tapi, orang m3muji film ini? Wajar karena orang tidak perduli tentang Batak. Orang hanya perduli tentang tontonan, bukan tentang tuntunan. (*)
*Budi P Hutasuhut adalah seorang penulis dan peneliti. Tulisan ini disalin dari postingan akun facebooknya : Budi P Hutasuhut, dan telah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk diterbitkan di media ini.